
Foto: http://kedaulatanpangan.net
oleh: Zulfadhli Nasution*
Jumlah populasi di area perkotaan negara-negara berkembang terus bertambah dalam beberapa dekade terakhir. Laporan FAO (2010) menunjukkan bahwa di awal abad ke-dua puluh satu, dua miliar manusia menduduki daerah perkotaan dan sejak saat itu jumlahnya melonjak hingga 2,5 miliar atau terhitung sama dengan lima kota Beijing baru setiap tahunnya. Laporan tersebut juga memprediksi bahwa di tahun 2025, lebih dari setengah populasi negara berkembang akan menjadi penduduk perkotaan dengan total 3,5 miliar. Dari negara-negara tersebut, negara dengan pendapatan rendah di Asia dan Afrika menjadi negara dengan pertumbuhan penduduk tercepat dengan proporsi pemuda yang besar, termasuk di Indonesia. Kompilasi data menunjukkan kenaikan penduduk perkotaan di Indonesia dari 42% di 2010, menjadi 50,7% di 2011, dan terakhir 53% di 2014 (FAO, 2013, 2014).
Tren tersebut dipandang oleh banyak negara dan organisasi sebagai salah satu tantangan besar untuk kecukupan pangan, termasuk bagi mereka yang hidup di daerah perkotaan. Penulis tidak secara sederhana berasumsi bahwa pertumbuhan penduduk adalah satu-satunya faktor pengancam kecukupan pangan sebagaimana kamp (Neo-)Malthusian membentuk wacana bahwa jumlah populasi dan sumber daya (termasuk pangan) selalu berbanding terbalik. Terdapat faktor lain bagi permasalahan tersebut yaitu kesetaraan akses dan distribusi pangan dalam era agrikultur yang industrialis. Bisa saja secara kuantitas ketersediaan pangan melimpah, tetapi dengan akses dan distribusi yang tidak merata, apalagi diiringi dengan harga yang tidak menentu, maka masyarakat tetap tidak bisa menjangkaunya.
Sejak tahun 1930-an hingga saat ini kebijakan pangan dunia didominasi oleh paradigma Produksionis, yang dalam beberapa hal telah berhasil meningkatkan jumlah produksi makanan, tetapi kelaparan masih terjadi dan berdampak setidaknya bagi 1,9 hingga 2,2 miliar manusia di seluruh dunia, baik yang secara langsung atau tidak langsung tidak tersentuh oleh paradigma tersebut. Di sisi lain, industrialisasi pangan yang dihasilkan dari paradigma tersebut telah mengubah karakteristik produksi pangan dari produksi skala kecil menjadi “produksi yang terkonsentrasi dengan distribusi massal yang juga membawa masalah kesehatan dan lingkungan serta membuat jarak antara produsen dan konsumen dengan rantai pasok pangan yang lebih panjang” (Lang and Heasman, 2004).
Terlebih lagi, beberapa kondisi berikut dapat menambah problematika produksi pangan di Indonesia. Jumlah rumah tangga pertanian yang sebagian besar tinggal di pedesaan sebagai produsen makanan utama untuk penduduk perkotaan, semakin berkurang. Dalam satu dekade terakhir, rumah tangga petani menurun dari 31,23 juta di 2003 menjadi 26,14 juta di 2013. Data statistik terakhir menunjukkan jumlah petani di Indonesia hanya berkontribusi terhadap 35% jumlah seluruh tenaga kerja, menurun dari 44% (BPS, 2014).
Walaupun total lahan pertanian cukup statis jika hitungannya seluruh wilayah, tetapi area perkotaan telah mengalami konversi lahan yang masif dari agrikultur menjadi peruntukan perumahan atau perkantoran dan industri, terlebih lagi di area yang berbatasan dengan Jakarta, juga Surabaya dan Bandung (Firman, 2000). Lahan yang terkonversi dari pemanfaatan agrikultur menjadi non-agrikultur mencapai setidaknya 56,000 – 60,000 hektar per tahun selama 2002 – 2010 (Kementerian Keuangan, 2014).
Laporan dari Badan Pusat Statistik juga menyatakan bahwa seiring dengan penurunan jumlah rumah tangga pertanian, industri agrikultur juga mulai untuk bertambah. Dari 4.000 perusahaan di 2003 jumlahnya meningkat menjadi 4.200 di 2013 dengan proporsi terbesar pada perusahaan perkebunan diikuti dengan peternakan dan tanaman pangan. Impor pangan juga membuat situasi menjadi rawan. Walaupun produktivitas tanaman pangan domestik juga meningkat, tetapi dalam lima tahun terakhir, jumlah impor pangan ke Indonesia telah terhitung dua kali dari total eskpornya (BPS, 2014).
Suara Kedaulatan Pangan
Belakangan, wacana “kedaulatan pangan” (Inggris: food sovereignty) mulai kerap kita dengar di berbagai media. Presiden Joko Widodo, sejak masa kampanyenya sudah menggaungkan hal tersebut sebagai salah satu program Nawacitanya. Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, juga telah menyebutkan istilah “kedaulatan pangan,” selain konsep yang selama ini lebih familiar yaitu “ketahanan pangan” (food security).
Dalam Undang-Undang Pangan disebutkan definisi kedaulatan pangan sebagai:
“hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.”
Secara formal, istilah “kedaulatan pangan” diluncurkan kepada publik di tahun 1996 ketika organisasi pendukung utamanya yaitu La Via Campesina menyatakan bahwa “ketahanan pangan” bukanlah sebuah jawaban untuk memastikan akses lokal bagi makanan yang sehat dan sesuai kultur masyarakat, karena selama ini hanya mengundang penafsiran kebijakan untuk memaksimalkan produksi pangan tanpa memperhatikan bagaimana, di mana, dan oleh siapa makanan tersebut diproduksi (Wittman, et al, 2010). Yang banyak diuntungkan dari kebijakan tersebut tentu saja adalah korporasi-korporasi besar dengan mekanisme impor-ekspor, rekayasa bioteknologi yang menggerus keanekaragaman produk lokal, dengan mekanisme penguasaan paten dan standardisasinya, dan bahkan mengkooptasi branding organik ataugreen.
Kedaulatan pangan mengekspresikan posisi yang bersebrangan dengan liberalisasi perdagangan dan mekanisme pasar bebas dalam sektor agrikultur (McMichael, 2014; Wittman, et al, 2010; Rosset, 2008) dan juga menentang rezim korporasi pangan (McMichael, 2014).
Kedaulatan pangan di Indonesia pertama kali dibawa oleh gerakan petani pedesaan di bawah keanggotaan La Via Campesina (di antaranya Serikat Petani Indonesia, SPI). Gerakan kedaulatan pangan yang berbasis pertanian pedesaan umumnya berperan dalam mempengaruhi aspek kebijakan pangan yang dikeluarkan pemerintah seperti resistensi terhadap impor beras yang masif, isu reformasi agraria, atau subsidi kepada petani gurem.
Dari sisi politik, masuknya istilah kedaulatan pangan dalam berbagai perangkat kebijakan merupakan suatu kemajuan. Tetapi pada praktek teknisnya, tentu saja membutuhkan upaya agar dapat terimplementasi di lapangan. Salah satu tantangan terkini yang penulis amati adalah untuk menyuarakan dan menggemakan suara kedaulatan pangan ke masyarakat perkotaan.
Kedaulatan Pangan dan Masyarakat Perkotaan
Kedaulatan pangan yang awalnya berfokus pada kedaulatan agrikultur pada tingkat nasional/negara (Jarosz, 2014), kemudian sebagai hasil dari pertemuan berbagai organisasi masyarakat sipil dan pertanian pada Deklarasi Nyeleni di Mali pada 2007 didefinisikan sebagai:
“hak bagi masyarakat terhadap pangan yang sehat dan sesuai dengan kultur yang dihasilkan melalui metode yang bergantung pada ekologi dan berkelanjutan, dan hak untuk mendefinisikan sistem pangan dan agrikultur mereka sendiri.”
Dari definisi teranyar ini, pangan yang sehat dan sesuai kultur adalah hak bagi (setiap) orang, dan bukan hanya (namun termasuk) dalam tingkat nasional. Dan dengan demikian, sebagai sebuah sistem, pangan melingkupi produsen, distributor termasuk konsumen.
Di berbagai negara lain, kedaulatan pangan sudah menjadi diskursus bagi kelas masyarakat perkotaan. McMichael (2014) menyatakan, bahwa kedaulatan pangan telah menginspirasi baik secara implisit dan/atau eksplisit berbagai komunitas, termasuk konsumen, pertanian skala kecil dan kelas penduduk urban untuk mengembangkan strategi adaptif yang berkaitan juga dengan pandangan kedaulatan pangan terhadap rezim pangan dan kerawanan pangan, entah mereka menyebutnya sebagai konsep kedaulatan pangan atau tidak.
Untuk mengambil perbandingan di Venezuela misalkan, dengan populasi yang didominasi oleh penduduk urban dan masyarakat non-agrikultur, tetapi mereka terlibat banyak dalam mengkonstruksikan kedaulatan pangan dengan menjembatani kerjasama antara kelompok perkotaan dan pedesaan. Selain dengan menciptakan pemasaran langsung antara produsen (pedesaan) dan konsumen (perkotaan), mereka juga menjadikan kedaulatan pangan sebagai kemauan politik (political will) bersama, sebagai contoh dengan menciptakan kerjasama dan kemitraan dalam rangkaian proses pangan mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi (Schiavoni, 2015). Dengan demikian, selain telah menempatkan kedaulatan pangan sebagai kebijakan nasionalnya, mereka juga telah selangkah lebih maju dengan melibatkan banyak pihak untuk membentuk sistem.
Hal inilah yang penulis lihat masih perlu upaya ekstra di Indonesia, untuk menyuarakan kedaulatan pangan di masyarakat perkotaan yang mulai mendominasi penduduk Indonesia, sementara jumlah petani (pedesaan) pun mulai berkurang. Bagaimana kedaulatan pangan dapat menawarkan idenya untuk mengatasi tantangan ini?
Penelitian penulis tahun 2015 terhadap beberapa komunitas pertanian perkotaan mengkonfirmasi bahwa kedaulatan pangan belum menjadi isu yang familiar, dan belum sebagai sikap yang kritis terhadap sistem yang dominan. Di sisi lain, gerakan petani pedesaan, seperti yang dikatakan perwakilan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), juga mengakui bahwa aspek tersebut belum jadi fokus, walaupun upaya ke arah tersebut sudah mulai ada.
“Sejujurnya, KRKP belum banyak mendorong (agenda) secara langsung ke perkotaan, tetapi kita coba untuk mulai memberi pengaruh pada konsumen, terutama anak-anak muda… Apabila hal tersebut bisa terorganisasi, memberikan pemahaman kepada mereka, meyakinkan mereka bahwa kedaulatan pangan juga bisa dimulai dari konsumen dan bukan hanya produsen, hal itu akan berdampak besar. Tetapi hal tersebut belum terjadi saat ini, masih terpisah (antara produsen dan konsumen)…” (Wawancara dengan Said Abdullah, Koordinator Advokasi dan Jaringan, KRKP).
Ada dua alasan setidaknya mengapa wacana kedaulatan pangan belum banyak beranjak ke masyarakat perkotaan. Pertama, kedaulatan pangan dan komunitas pangan urban memiliki latar belakang dan akar historis yang berbeda. Gerakan kedaulatan pangan pertama kali muncul di akhir 1900-an daripada tren komunitas pangan perkotaan seperti urban farming yang baru muncul sekitar lima tahun lalu. Memang terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997 – 1998 yang membuat pertanian perkotaan juga menjamur di DKI Jakarta, tetapi sebagai aksi yang tidak terorganisasi, dan sebagai penyangga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin kota, terutama mereka yang bermigrasi dari provinsi lain ke Jakarta (Purnomohadi, 1999).
Dengan demikian, yang kedua, komunitas urban (farming) juga memiliki karakteristik pandangan sosial politik yang berbeda dengan organisasi pertaniaan pedesaan sebagai tempat bagi mayoritas ide-ide kedaulatan pangan saat ini. Inisiatif komunitas urban farming kebanyakan muncul dari pemuda dengan karakter pendidikan tinggi dan ekonomi menengah yang mengikuti tren sosial media dengan isu yang banyak beredar di kalangan mereka seputar kota yang berkelanjutan dan hijau. Dalam beberapa hal, diakui pula bahwa telah terjadi depolitisasi di kalangan masyarakat kota sejak era order baru, dan pandangan politik ekonomi menjadi minoritas di kalangan menengah perkotaan (wawancara dengan Zainal Arifin Fuad, Koordinator Hubungan Luar Negeri, Serikat Petani Indonesia), terutama yang berkaitan dengan aspek lain di luar isu pemerintahan, pemilihan umum, partai politik per se.
Seharusnya perbedaan tersebut tidak menjadi masalah sebagai langkah awal bagi gerakan pangan yang mulai memasuki perkotaan, karena kedaulatan pangan merupakan “hak bagi semua orang…” untuk mendapatkan pangan yang sehat dan sesuai secara kulur, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, masyarakat, kelompok suku bangsa, kelas sosial ekonomi dan generasi” (Nyeleni Declaration, 2007).
Mempertimbangkan kondisi tersebut di Indonesia, penulis berpendapat bahwa saat ini masih merupakan tahap awal dari transisi gerakan pangan memasuki kelompok perkotaan dan konsumen, yang selanjutnya, menjadi kesempatan terbuka bagi kedaulatan pangan untuk menyertakan prinsip dan prakteknya, tanpa harus menyebutnya secara eksplisit. Gerakan transisi, sebagaimana disampaikan oleh Sage (2014) memiliki berbagai kecenderungan, tetapi satu hal yang penting adalah upaya untuk membangun gaya hidup alternatif, mulai dari yang paling jauh melepaskan diri dari pasar dengan penyediaan pangan mandiri atau memainkan peran sebagai “sarana untuk mobilisasi sosial, resiliensi komunitas, pelibatan masyarakat dan juga potensi solidaritas trans-nasional.”
Pada akhirnya ada beberapa hal yang menjadi saran dalam penelitian yang penulis lakukan sebagai refleksi bagi komunitas perkotaan dan gerakan kedaulatan pangan di tataran praktis, selain dalam proses mempengaruhi kebijakan. Di antaranya:
- Dibutuhkan gerakan kedaulatan pangan yang lebih inklusif bagi populasi perkotaan, sedangkan komunitas urban pun harus merefleksikan gerakannya untuk lebih kritis terhadap sistem pangan industrialis saat ini. Gerakan kedaulatan pangan sebaiknya memperhatikan perbedaan karakteristik (latar belakang sosial-ekonomi, pandangan politik pangan) dari masyarakat perkotaan dengan membuat mekanisme yang sesuai dengannya tanpa melupakan edukasi prinsip-prinsip kedaulatan pangannya.
- Sementara konsumen urban juga sebaiknya membangun juga konsumerisme reflektif dan mau untuk membangun solidaritas dengan produsen pangan dari pedesaan.
Cara yang moderat adalah dengan mencari bonding issue yang sama sebagai awalan seperti makanan lokal atau organik karena populasi urban mungkin memiliki kebutuhan dan kultur yang berbeda, walaupun kemudian perlu untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentang nilai-nilai kedaulatan pangan (wawancara SPI dan KRKP). Untuk ini, diperlukan pelibatan dengan cara-cara kreatif dari berbagai kelompok konsumen termasuk kelompok berbasis kuliner lokal, gerakan Slow Food, dan lain-lain. Kelompok-kelompok ini juga dapat mempromosikan hubungan dengan sumber daya pangan dari petani desa termasuk produk hilirisasi mereka, dan membangun kemitraan dalam menyebarkan ide kedaulatan pangan (wawancara dengan KRKP).
Contoh lainnya, mereka bisa mengadakan semacam “tur kedaulatan pangan” dengan mengunjungi salah satu area dengan praktek terbaik sekaligus mempertemukan gerakan pedesaan dan perkotaan.
Hal ini sejalan dengan argumen yang dikemukakan Francis, dkk (2003) yang dinamakan “closing a loop” dengan mengedukasi konsumen mengenai pola pertanian berkelanjutan yang sering terlupakan, bahkan sudah tidak dipedulikan oleh masyarakat perkotaan secara umum. Secara bertahap, konsumen harus diedukasi mengenai hubungan antara makanan mereka, pertanian, kesehatan dan lingkungan. Setelah mereka terpapar informasi, mereka akan lebih menerima terhadap isu-isu berkaitan dengan sistem pangan lokal, komunitas, termasuk pemahaman tentang kondisi pertanian, pengomposan, produk organik dan community supported agriculture termasuk fungsi dan layanan ekosistem yang lebih kompleks.
Di samping itu, edukasi konsumen harus menyertakan tentang bagaimana pertanian dapat dilakukan dengan sistem yang berkelanjutan tanpa pupuk dan pestisida kimia di saat yang sama juga mereka melindungi ekosistem yang berperan sebagai penjaga lingkungan, dan memberi perhatian terhadap kesehatan dan keamanan pangan konsumen. Dengan demikian,
“Konsumen dapat diyakinkan ketika mereka melakukan pilihan untuk membeli makanan yang diproduksi dengan cara demikian. Edukasi lebih lanjut tentang bagaimana makanan diproduksi, dari mana, oleh siapa, dan dalam kondisi apa akan mempengaruhi keputusan mereka” (ibid).
Referensi:
BPS (2014). Potensi Pertanian Indonesia: Analisis Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013. Jakarta: Badan Pusat Statistik
FAO (2014). Food and Nutrition in Number 2014. Rome: Food and Agriculture Organization.
FAO (2013). FAO Statistical Yearbook 2013: World food and Agriculture. Rome: Food and Agriculture Organization
FAO (2010). Growing Greener Cities. Rome: Food and Agriculture Organization
Firman, T. (2000) ‘Rural to Urban Land Conversion in Indonesia during Boom and Bust Periods’, Land Use Policy 17(1): 13-20.
Francis, C., S. Simmons, C. Flora, G. Lieblein, S. Gliessman, R. Poincelot et al. (2003) ‘Agroecology: The Ecology of Food Systems’, Journal of Sustainable Agriculture 22(3): 99-118.
Jarosz, L. (2014) ‘Comparing Food Security and Food Sovereignty Discourses’, Dialogues in Human Geography 4(2): 168-181.
Kementerian Keuangan (2014) ‘Pengaruh Konversi Lahan Terhadap Produk Pertanian’ accessed 14 May 2015 <http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/edef-konten-view.asp?id=20141231133159478508722>
Lang, T. and M. Heasman (2004) Food Wars: The Global Battle for Mouths, Minds and Markets / Tim Lang and Michael Heasman. London [etc.]: Earthscan.
McMichael, P. (2014) ‘Historicizing Food Sovereignty’, Journal of Peasant Studies 41(6): 933-957.
Nasution, Zulfadhli (2015) ‘Indonesian Urban Farming Communities and Food Sovereignty’ Research Paper, International Institute of Social Studies, the Hague.
Purnomohadi N. (2001) ‘Urban agriculture as an alternative strategy to face the economic crisi’ in N Bakker, M Dubbeling, S Guendel, US Koschella, H de Zeeuw (eds.). Growing cities growing food: Urban agriculture on the policy agenda, 453-465. Leusden: RUAF., Publication.
Rosset, P. (2008) ‘Food Sovereignty and the Contemporary Food Crisis’, Development 51(4): 460-463
Sage, C. (2014) ‘The Transition Movement and Food Sovereignty: From Local Resilience to Global Engagement in Food System Transformation’, Journal of Consumer Culture 14(2): 254-275.
Schiavoni, C.M. (2015) ‘Competing Sovereignties, Contested Processes: Insights from the Venezuelan Food Sovereignty Experiment’, Globalizations : 1-15.
Wittman, H., A.A. Desmarais, N. Wiebe (2010) “The Origins and Potential of Food Sovereignty” in H. Wittman, A.A. Desmarais, N. Wiebe (eds.)Food Sovereignty: Reconnecting Food, Nature and Community, 1-14. Oxford: Pambazuka.
* Zulfadhli Nasution merupakan peneliti independen; alumni Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Padjadjaran dan International Institute of Social Studies, Den Haag, program Agrarian, Food and Environmental Studies
** Tulisan disarikan dari tesis penulis dalam menyelesaikan dua program studi di atas.
Sumber: http://kedaulatanpangan.net/


 BITRA Indonesia, Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia
BITRA Indonesia, Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia 
 Hadi Siswoyo: Penggagas Ekonomi Kolektif dari Air Hitam
Hadi Siswoyo: Penggagas Ekonomi Kolektif dari Air Hitam 
 Pengobatan Alternatif: Murah Sehat
Pengobatan Alternatif: Murah Sehat 
 Mendulang Harap di Air Hitam
Mendulang Harap di Air Hitam 
 Membangun Kemandirian Ekonomi
Membangun Kemandirian Ekonomi 
 Kuala Namu: Suara Dari Balik Tembok (Part-1)
Kuala Namu: Suara Dari Balik Tembok (Part-1) 
 Kuala Namu (Perjuangan Menembus Batas) Part - 1
Kuala Namu (Perjuangan Menembus Batas) Part - 1 
 Environmentally Sustainable Plantation (Kebun Tanaman Campuran Polikultur)
Environmentally Sustainable Plantation (Kebun Tanaman Campuran Polikultur) 
 Kuala Namu (Perjuangan Menembus Batas) Part - 2
Kuala Namu (Perjuangan Menembus Batas) Part - 2 
 BARA TANAH RAMUNIA
BARA TANAH RAMUNIA 
 Kuala Namu: Penerbang Dari Balik Tembok (Part-2)
Kuala Namu: Penerbang Dari Balik Tembok (Part-2) 
 Kuala Namu (Perjuangan Menembus Batas) Part - 3
Kuala Namu (Perjuangan Menembus Batas) Part - 3 
 Kuala Namu: Penerbang Dari Balik Tembok (Part-1)
Kuala Namu: Penerbang Dari Balik Tembok (Part-1) 
 Kuala Namu: Suara Dari Balik Tembok (Part-2)
Kuala Namu: Suara Dari Balik Tembok (Part-2) 
 Liputan Reog Cilik MITRA FM
Liputan Reog Cilik MITRA FM 
 Gerakan Penghijauan MITRA FM 107,7 MHz
Gerakan Penghijauan MITRA FM 107,7 MHz 
 MITRA FM dalam National Forest Program - Food and Agriculture Organization (NFP-FAO)
MITRA FM dalam National Forest Program - Food and Agriculture Organization (NFP-FAO) 
 Pelatihan Pemanfaatan Mangrove MITRA FM 107,7 MHz
Pelatihan Pemanfaatan Mangrove MITRA FM 107,7 MHz 
 Semangat Berkarya
Semangat Berkarya 
 Gending Jawa di tanah Sumatera
Gending Jawa di tanah Sumatera 
 Reog Ponorogo di Sumatra
Reog Ponorogo di Sumatra 
 menitip mati (the revolution is)
menitip mati (the revolution is) 
 BITRA Indonesia, 25 Tahun Bersama Rakyat
BITRA Indonesia, 25 Tahun Bersama Rakyat 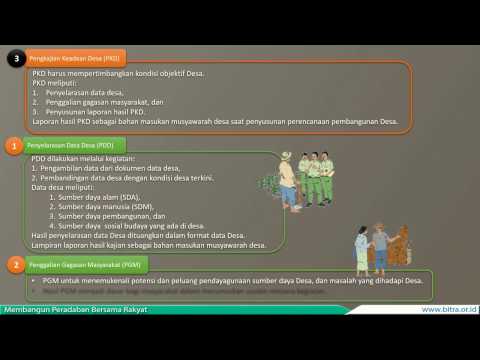
 Penyusunan RPJM Desa, UU Desa 6/2014 & Permendagri 114/2014
Penyusunan RPJM Desa, UU Desa 6/2014 & Permendagri 114/2014 
 Profil Desa Tanjung Harap
Profil Desa Tanjung Harap 
 Cara Penyusunan Perdes (Videoslide)
Cara Penyusunan Perdes (Videoslide) 
 Belajar SID ke Jogja
Belajar SID ke Jogja 
 BITRA Gelar Konsultasi Publik Ranperda Perlindungan Pekerja Rumahan
BITRA Gelar Konsultasi Publik Ranperda Perlindungan Pekerja Rumahan 
 Implementasi UU Desa (TVRI Sumut)
Implementasi UU Desa (TVRI Sumut) 













